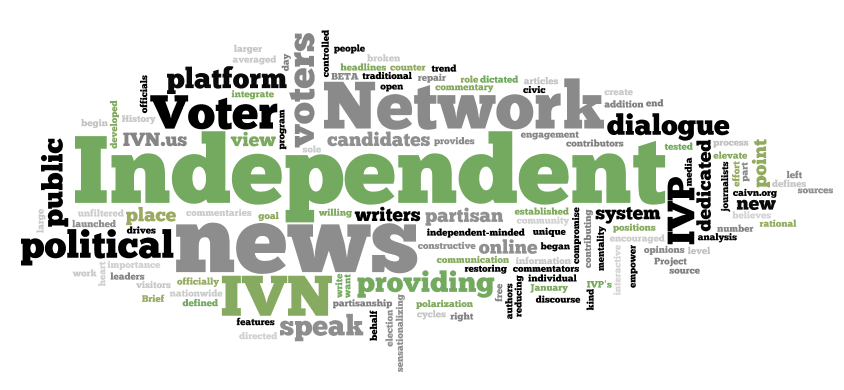Drs.Ec. H. Eko Walujo Suwardyono, MM – Komisioner KPU Kota Surabaya Periode 2009-2014
“Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.” [QS. Al-Furqon (25:63)]
I. PENDAHULUAN
Disadari atau tidak, komunikasi selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Bahkan sejak bayi dalam kandungan dan tangisan saat lahir, itu menjadi tanda komunikasi. Secara khusus, komunikasi merupakan hubungan kontak antara sesama manusia selaku individu maupun kelompok (organisasi). Dalam kenyataannya sering dijumpai berbagai konflik yang menjurus konflik yang merusak dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai contoh ‘kecil’ dilingkungan organisasi, yaitu ketika sistem administrasi dan pengambilan keputusan menjadi terhambat karena kesalahan komunikasi. Jika dibiarkan, pada gilirannya akan merusak sistem organisasi dan kelangsungan hidup organisasi itu sendiri.
Setiap manusia mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda meskipun seorang anak lahir kembar identik. Karena itu Islam mengatur tatacara dan etika bergaul sehingga mampu berinteraksi sinergis dengan orang lain. Berdasarkan arti firman Allah dalam QS. Al-Furqon diatas, maka sikap tawadhu’ (rendah hati) serta pengucapkan kata-kata yang baik (Qaulan Salaamah) dalam hubungannya dengan orang lain merupakan sikap berkomunikasi yang sangat mulia.
Sabda Rasulullah: “Sesungguhnya Allah telah memberi wahyu kepadaku, yaitu engkau sekalian hendaklah bersikap tawadhu sehingga tidak ada seseorang bersikap sombong kepada yang lain, dan tidak ada seseorang yang menganiaya yang lain.” [HR. Muslim]. Dalam riwayat lain Anas RA berkata: “Bila ada budak di Madinah memegang tangan Nabi SAW, maka beliau pergi mengikuti kemana budak itu menghendaki.” [HR. Bukhari]. Dari kedua hadits ini tampak jelas ketauladanan Rasulullah terhadap sikap tawadhu’ dengan tidak membedakan status sosial.
Tulisan ini tidak membahas berbagai konsep, teori dan metode komunikasi secara pragmatis atau teknis maupun bentuk studi kasus. Tulisan ini hanya tinjauan ulang tentang prinsip pengembangan komunikasi efektif berdasarkan kaidah Rahmatan Lil ‘Alamin serta konsep dasar teori pengembangan komunikasi efektif pragmatis yang sesuai. Dengan kata lain, tulisan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan komunikasi efektif yang berakar pada perspektif Rahmatan Lil ‘Alamin.
II. PRINSIP KOMUNIKASI RAHMATAN LIL ‘ALAMIN
Komunikasi dalam prinsip Rahmatan Lil ‘Alamin ditujukan untuk mewujudkan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT dan hubungan horisontal antar sesama manusia. Hubungan vertikal dilakukan dengan amal ibadah, sedangkan komunikasi horisontal melalui amal shalih di berbagai bidang seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, dan seni. Muara dari dua sisi komunikasi tersebut adalah meningkatnya ketaqwaan dan juga terbentuknya transformasi masyarakat yang lebih baik dalam naungan prinsip Rahmatan Lil ’Alamin (membawa rahmat bagi semua).
Sudah tentu komunikasi berdasarkan prinsip Rahmatan Lil ‘Alamin ini sangat berbeda dengan konsep komunikasi dalam perspektif pemikiran‘Barat’. Prinsip ini cenderung memandang komunikasi dari sisi pragmatis, materialistik-duniawi dan menekankan pada kapitalisme semata. Pesan dalam kegiatan komunikasi diarahkan pada capaian keuntungan secara materi baik antar individu maupun mengeruk keuntungan melalui sarana komunikasi massa seperti media cetak maupun elektronik. Aspek moral dan etika cenderung terabaikan, sehingga berbagai produk komunikasi yang dihasilkan seringkali membawa dampak negatif yang besar.
Komunikasi sesuai dengan prinsip Rahmatan Lil ‘Alamin sangat mengutamakan etika, keakuratan informasi serta pertanggung-jawaban. Hal ini juga telah diatur dalam Al Qur’an, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ali Imran [3: 159], Surat Al Hujarat [49: 6] dan Surat Al-Isra’ [17: 36]:
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma`afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu . Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” [QS. Ali Imran (3:159)]
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” [QS. Al-Hujurat (49:6)]
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” [QS. Al-Isra’ (17: 36)]
Prinsip-prinsip dalam Al Qur’an tersebut bisa disarikan menjadi tiga konsep yaitu (1). Qawlan Sadidan, (2). Qawlan Balighan, dan (3). Qawlan Layyinan. Qawlan Sadidan artinya pembicaraan yang benar, jujur, lurus, tidak bohong, tidak berbelit-belit. Benar artinya sesuai dengan kriteria kebenaran Al-Qur’an dan Al-Sunnah baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Qawlan Balighan yang berasal dari kata “baligh” yang artinya sampai, mengenai sasaran, atau menciptakan tujuan. Ini berarti pembicaraan harus jelas maknanya, serta tepat dalam pengungkapannya. Oleh karena itu dalam konsep Qawlan Balighan, dapat diterjemahkan sebagai prinsip komunikasi yang efektif. Konsep ketiga yaitu Qawlan Layyinan, yang berarti perkataan yang lembut yaitu mengedepankan persuasi dan mengarahkan pada solusi yang bijaksana.
III. KOMUNIKASI EFEKTIF PRAGMATIS
Menurut Steward L. Tubbs dan Sylvia Moss dalam bukunya “Human Communication” (1999), komunikasi dianggap efektif apabila menghasilkan 5 hal: (1) pengertian, (2) kesenangan, (3) pengaruh pada sikap, (4) hubungan sosial yang makin baik, dan (5) tindakan nyata. Yang dimaksud dengan ‘pengertian’ adalah terdapatnya penerimaan yang baik dari isi pesan sebagaimana yang dimaksud oleh sumber pesan. Kemudian, komunikasi disebut efektif jika menghasilkan kesenangan bagi penerima pesan, seperti ucapan “Apa kabar?”. Komunikasi seperti ini yang menyebabkan hubungan yang penuh keakraban dan kehangatan. Komunikasi juga disebut efektif jika menghasilkan perubahan sikap melalui ajakan secara persuasif dari pemberi pesan kepada penerima pesan.
Selanjutnya komunikasi efektis harus mampu meningkatkan kualitas hubungan sosial yang makin baik. Penelitian dari ahli bidang psikologi Philip G. Zimbardo dari Stanford University (1978) membuktikan bahwa kurangnya komunikasi menyebabkan seseorang bersifat lebih agresif, sering merusak dan berkurangnya rasa bertanggung jawab. Sebelumnya, Vance Packard (1974) juga menyatakan bahwa kegagalan komunikasi untuk menumbuhkan hubungan interpersonal dapat menyebabkan seseorang menjadi: agresif, senang merusak, senang berkhayal, ‘dingin’, sakit fisik dan mental serta terkena ‘flight syndrome’ (melarikan diri dari lingkungannya). Selanjutnya keseluruhan proses komunikasi akan menjadi efektif jika pada akhirnya menghasilkan tindakan nyata dari penerima pesan.
Menurut Steven R. Covey, dalam bukunya “The 7 Habits of Highly Effective People” (1989): “The single most important principle in the field of interpersonal relations is this: Seek first to understand, then to be understood. Most people listen, not with the intent to understand, but with the intent to reply”. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hubungan intrapersonal faktor yang terpenting adalah sikap seseorang untuk berupaya mengerti orang lain lebih dahulu, baru kemudian meminta diri sendiri dimengerti. Steven R. Covey mengusulkan 5 (lima) pondasi membangun komunikasi efektif :
1. BERUSAHA MENGERTI ORANG LAIN
Ini adalah dasar dari apa yang disebut emphatetic communication (komunikasi empatik). Bentuk komunikasi tertinggi adalah komunikasi empatik, yaitu melakukan komunikasi untuk terlebih dahulu mengerti orang lain, memahami karakter dan maksud tujuan atau peran orang lain. Kebaikan dan sopan santun yang kecil-kecil begitu penting dalam suatu hubungan, sehingga “hal-hal yang kecil adalah hal-hal yang besar”.
2. MEMENUHI KOMITMEN ATAU JANJI
Melanggar janji adalah kesalahan yang terbesar
3. MENJELASKAN HARAPAN
Penyebab dari hampir semua kesulitan dalam hubungan berakar di dalam harapan yang bertentangan atau berbeda sekitar peran dan tujuan. Harapan harus dinyatakan secara eksplisit.
4. MINTA MA’AF SECARA TULUS JIKA TERJADI KESALAHAN
Meminta maaf ketika kita membuat kesalahan bukanlah perbuatan yang memalukan. Cobalah untuk mengakui kesalahan kita dan meminta maaf secara tulus. Ini perbuatan terpuji.
5. MENUNJUKKAN INTEGRITAS PRIBADI
Integritas merupakan pondasi utama dalam membangun komunikasi yang efektif. Karena tidak ada pesahabatan atau teamwork tanpa ada kepercayaan (trust), dan tidak akan ada kepercayaan tanpa ada integritas. Integritas mencakup hal-hal yang lebih dari sekadar kejujuran (honesty). Kejujuran mengatakan kebenaran atau menyesuaikan kata-kata dengan realitas. Integritas menyesuaikan realitas dengan kata-kata kita. Integritas bersifat aktif, sedang kejujuran bersifat pasif.
IV. KESIMPULAN
Konteks pengembangan komunikasi efektif hendaknya dikembalikan pada akar hakikat kehidupan manusia yang Rahmatan Lil ’Alamin. Hal itu untuk mencegah terjadinya ekses proses komunikasi yang tidak dikehendaki, khususnya etika dan moralitas. Dengan demikian keharusan untuk berpegang pada proses komunikasi yang penuh dengan sikap tawadhu’, memahami etika komunikasi, keakuratan informasi dan pertanggung-jawaban (kepada Allah SWT dan sesama) menjadi prinsip komunikasi efektif yang tidak boleh ditinggalkan.
Upaya untuk melakukan pengembangan komunikasi efektif baik secara individu maupun kelompok (organisasi) perlu dilakukan terus menerus. Hal ini mengingat visi dan misi individu dan kelompok hakikatnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Karena itu, evaluasi kinerja individu dan kelompok (organisasi) sudah seharusnya tidak mengabaikan komunikasi efektif sebagai faktor penentu yang sangat penting.
Surabaya, 6 Februari 2012
Tulisan ini juga dimuat dalam majalah HALOKPU Edisi I, Maret 2012